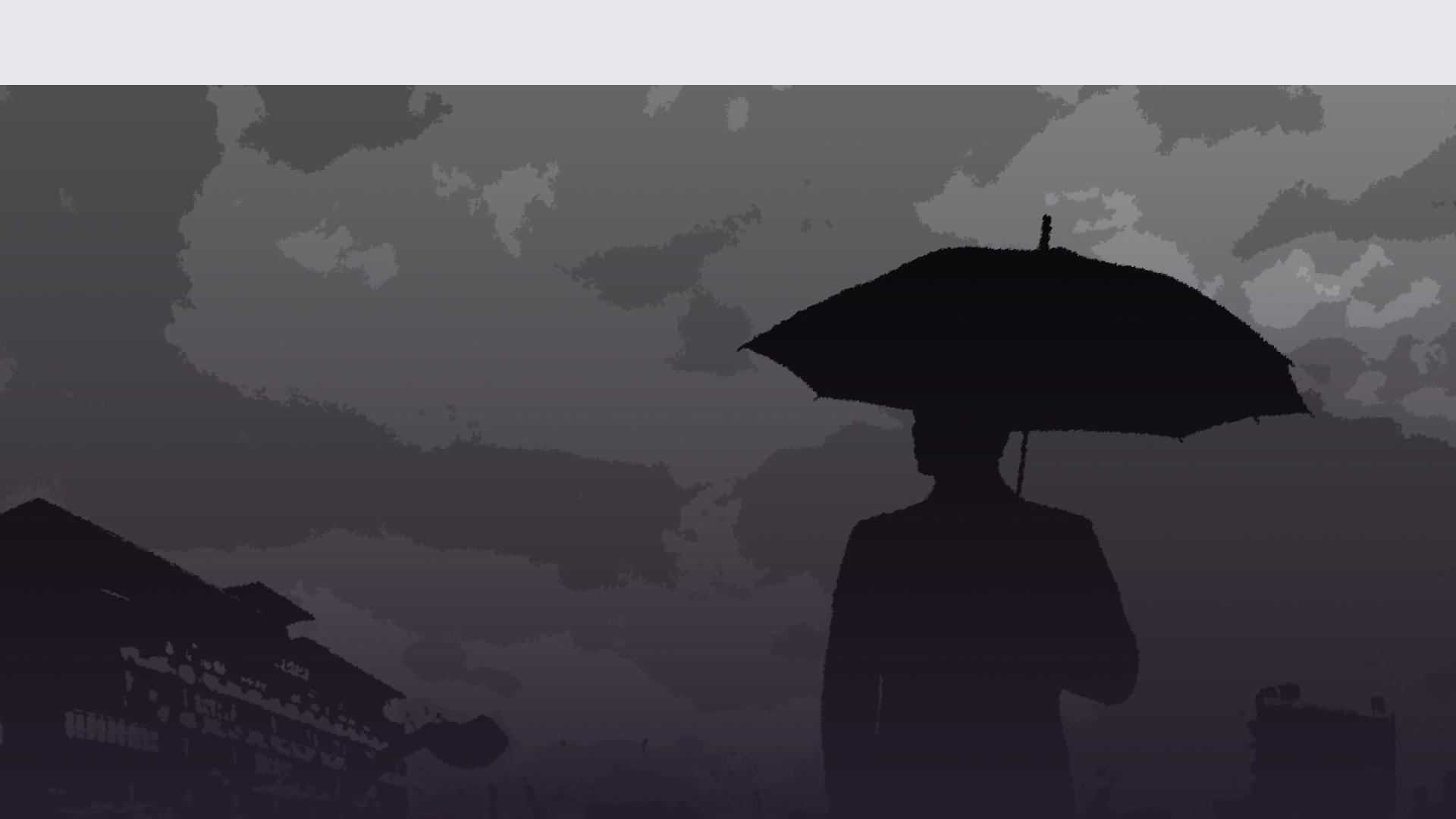Tragedi, Fase Respon, dan Reaksi Emosional
Peristiwa ambruknya musala Ponpes Al Khoziny terjadi pada Senin, 29 September 2025. Peristiwa ini bermula saat lebih dari 100 santri tengah melaksanakan salat Ashar berjamaah pukul 15.00 WIB di musala yang bertempat di lantai 2 gedung. Namun, saat memasuki rakaat kedua, bangunan sempat bergoyang untuk kemudian runtuh. Salah satu santri kelas 7 Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang selamat mengaku bahwa ia melihat bagian ujung musala tersebut ambruk. Sementara itu, Ketua RT 07/RW 03 Desa Buduran, mengaku mendengar suara keras saat bangunan tersebut roboh (Kompas, 2025). Beberapa korban berhasil menyelamatkan diri namun banyak yang tertimpa reruntuhan dan mengalami luka-luka. Sejauh ini, dari total 67 kantong jenazah, 50 di antaranya telah berhasil diidentifikasi (Detik, 2025). Kapolda Jateng menduga penyebab utama dari ambruknya gedung dikarenakan adanya kegagalan konstruksi. Situasi ini mendorong dilibatkannya ahli teknik sipil dan ahli bangunan untuk memberikan analisis secara resmi (BBC, 2025).
Menurut Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), respon psikologis terhadap bencana berkembang melalui 6 fase emosional, meliputi fase pra-bencana, fase dampak, fase heroik, fase bulan madu, fase kekecewaan, dan fase rekonstruksi (Tulane University, 2021).
Pada fase pra-bencana, individu mungkin merasa rentan dan hilangnya rasa kendali, terutama jika bencana terjadi tanpa peringatan. Sebaliknya, jika tanda-tanda bahaya telah muncul sebelumnya, bisa timbul rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri karena tidak mempedulikan peringatan yang ada (Children’s Hospital Association, 2021). Hal ini tercermin pada peristiwa ambruknya musala pondok pesantren Al Khoziny, diketahui seorang santri sempat mengingatkan bahwa bangunan di atas mulai bergerak tidak stabil. Namun informasi tersebut tak sempat sampai ke para pengurus musala, lantaran sebagian besar sedang melaksanakan salat ashar (liputan6, 2025).
Ketika bencana menjadi nyata, fase dampak muncul ditandai dengan perasaan takut dan tidak percaya. Responsnya bisa sangat bervariasi, tergantung pada sifat bencana dan mekanisme koping pribadi seseorang. Salah satu korban selamat menceritakan bahwa selama 3 hari terjebak dalam reruntuhan, ia hanya bisa tidur dan bangun dalam kegelapan, tanpa tahu waktu pagi atau malam (detikJatim, 2025). Setelah fase ini, muncul fase heroik dimana orang-orang menjadi panik sehingga banyak aktivitas yang belum tentu produktif (Tomkins, 2025). Dalam kasus yang sama, terdapat penyintas berhasil membantu lima santri lain untuk keluar sebelum akhirnya berhenti karena khawatir bangunan akan kembali runtuh (liputan6, 2025).
Selanjutnya, fase bulan madu muncul. Fase ini dikaitkan dengan kohesi komunitas bahwa mereka akan pulih, baik-baik saja, serta bisa “melewati ini bersama-sama” (Tompkins, 2025). Setelah optimisme menurun, penyintas masuk ke fase kekecewaan, fase ini menjadi fase terlama tahap pemulihan yang terjadi ketika seseorang telah berusaha keras, tetapi tidak yakin kapan akan selesai. Lalu, muncul rasa putus asa dengan tingkat emosi berada pada titik terendahnya (Gutierrez, 2022). Akhirnya, fase rekonstruksi menjadi tahap dimana penyintas muncul perasaan pulih seutuhnya. Orang-orang bertanggung jawab memikul kembali kehidupan mereka dan menyesuaikan diri dengan keadaan normal yang baru sambil berduka (Children’s Hospital Association, 2021).
Psychological First Aid
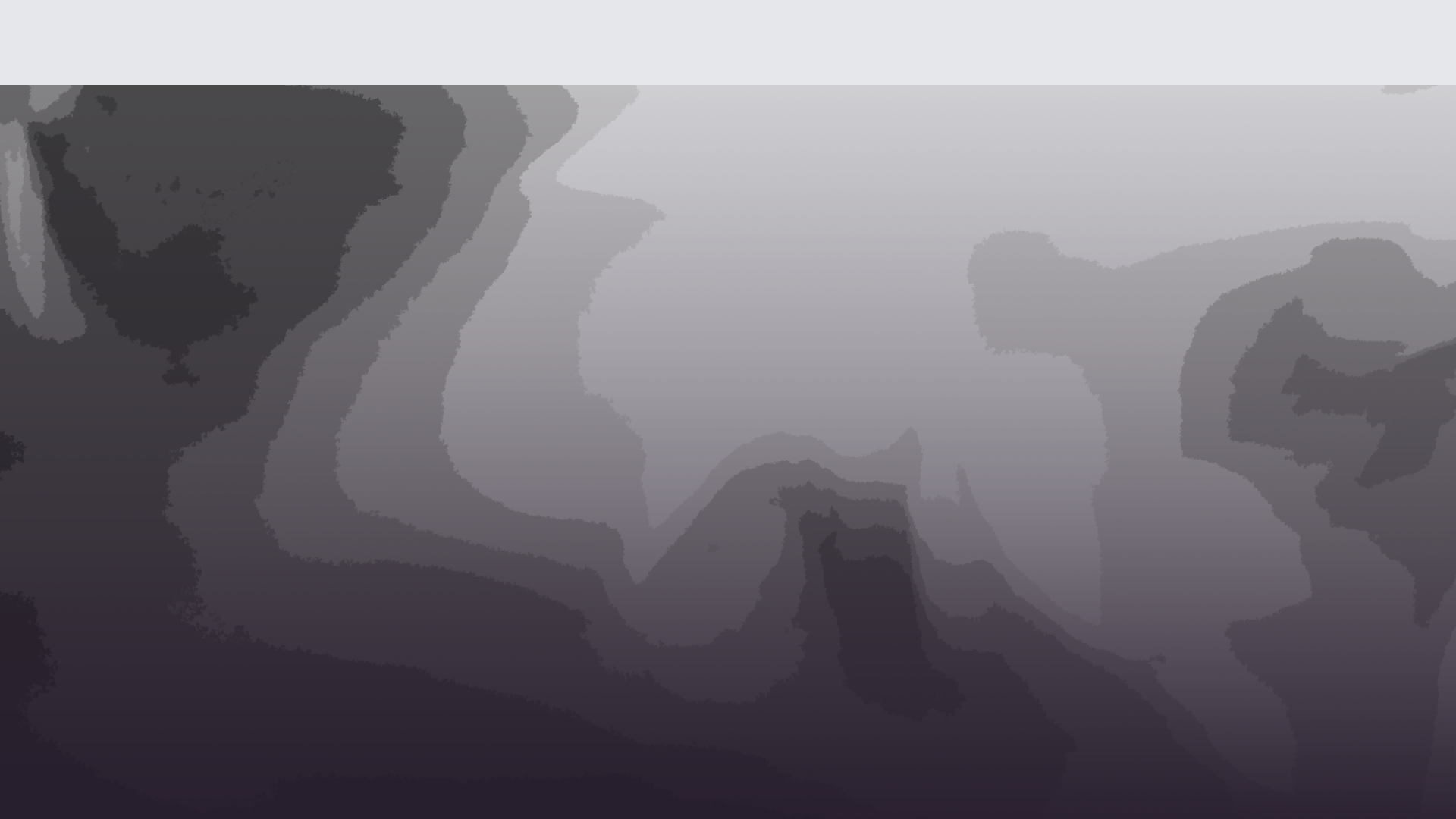
Pendekatan Psychological First Aid (PFA) sebagaimana dijelaskan oleh Brymer et al., (2006), menjadi strategi dalam mendampingi korban bencana. Tahap stabilisasi bertujuan membantu penyintas yang mengalami disorientasi, kepanikan, atau kewalahan emosional agar kembali tenang dan mampu memahami situasi di sekitarnya. Sementara itu, tahap mitigasi berfokus pada upaya mencegah memburuknya stres psikologis dan meminimalkan risiko munculnya dampak jangka panjang, seperti trauma atau gangguan fungsi sehari-hari.
Dalam peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny, penerapan dua tahap ini menjadi sangat krusial mengingat sebagian besar korban adalah remaja santri. Relawan atau pendamping dapat membantu menenangkan korban yang menangis atau tampak kebingungan, berbicara dengan nada lembut, serta membantu mereka bernafas perlahan atau berfokus pada hal konkret/nyata di sekitar. Setelah kondisi emosional lebih terkendali, pemberian informasi yang jelas tentang situasi dan proses evakuasi, dan dukungan sosial dapat membantu santri mengatasi reaksi awal terhadap bencana, serta mencegah munculnya stres atau ketakutan berkepanjangan setelah peristiwa tersebut.
“Jangan langsung kasih saran atau bilang "sudahlah, ikhlas aja" justru itu gak baik buat perasaan mereka. Biarkan mereka cerita kalau mereka mau, tapi jangan dipaksa kalau mereka belum siap. Hindari juga pertanyaan yang terlalu invasif atau minta mereka cerita detail traumatis, karena bisa bikin trauma lagi.” -anonim
Tahap selanjutnya yaitu pemulihan, bertujuan membantu penyintas membangun kembali rasa kendali, harapan, dan kemampuan beradaptasi setelah peristiwa krisis. Aktivitas ringan seperti doa bersama, belajar kelompok sederhana, atau kegiatan sosial dapat membantu memberi makna positif, sehingga mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi tersebut. Selain itu, memberikan ruang bagi santri untuk mengekspresikan perasaan mereka secara aman, baik melalui percakapan, menulis, maupun aktivitas kreatif dapat membantu proses pemulihan emosional dan memperkuat ketahanan psikologis mereka pasca-bencana.
“Tantangan terbesar adalah menaikkan kembali harapan dan motivasi. Tentu ada yang namanya survival instinct ketika terjadinya bencana, namun tidak sedikit kejadian bukannya survival instinct tetapi rasa keputusasaan yang mendorong masyarakat untuk putus asa/pasrah dengan keadaan terutama bagi mereka yang dirinya/saudara terluka parah ataupun kehilangan.” -anonim
Apabila ditemukan tanda-tanda gangguan psikologis berat seperti mimpi buruk berulang, ketakutan ekstrem, atau penarikan diri sosial, maka diperlukan tahap rujukan kepada tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Relawan dan pendamping perlu mampu mengenali tanda-tanda tersebut dan menghubungkannya dengan layanan kesehatan mental yang sesuai. Koordinasi dengan pihak sekolah, keluarga, serta lembaga terkait sangat penting agar proses rujukan berjalan lancar dan tidak menimbulkan stigma. Berbagai reaksi emosional dan proses pemulihan ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana perlu dibangun tidak hanya pada individu, tetapi juga pada tingkat lembaga agar dapat meminimalkan dampak psikologis di masa depan.
Peristiwa ambruknya Ponpes Al Khoziny menjadi contoh nyata bagaimana bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan dampak luas, baik fisik maupun psikologis. Peristiwa ini menegaskan pentingnya kesadaran risiko di lingkungan pendidikan.
Secara sosial, kesadaran terhadap bahaya sering dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan kolektif. Wang (2022) menyebut bahwa pandangan fatalistik dapat menurunkan persepsi terhadap risiko. Temuan ini sejalan dengan Hargono et al. (2023) yang menemukan bahwa masyarakat dengan kesadaran rendah memiliki risiko 1,49 kali lebih besar untuk tidak siap menghadapi bencana. Peristiwa ambruknya musala Ponpes Al Khoziny menjadi salah satu contoh peristiwa penting dalam mempersiapkan kesiapan psikologis dalam menghadapi bencana secara tiba-tiba. Melalui pemahaman enam fase respon bencana, mulai dari pra-bencana hingga rekonstruksi, dapat terlihat bagaimana individu maupun komunitas dapat melalui perubahan emosi yang kompleks, dari kepanikan hingga akhirnya bisa pulih dan mampu beradaptasi. Dalam konteks ini, penerapan Psychological First Aid (PFA) dapat menjadi suatu hal yang krusial untuk membantu dalam menstabilkan kondisi emosional korban, mencegah dampak psikologis jangka panjang, serta membantu proses pemulihan mental secara bertahap.
Sebagai tindakan pencegahan, Yildiz et al. (2023) membuktikan bahwa pendidikan kebencanaan dapat meningkatkan persepsi risiko dan kesiapsiagaan anak-anak. Artinya, awareness bukan hanya soal mengetahui bahaya, tetapi membangun kesiapan mental dan sosial santri untuk bertindak demi keselamatan bersama. Dengan demikian, awareness dalam hal ini tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi pada sistem pendidikan untuk membangun kesiapsiagaan dan keselamatan bersama.
● Apa kata mahasiswa? ●
“... yang paling penting itu audit rutin bangunan secara berkala, jangan cuma cek akreditasi. Jadi gak cuma melakukan akreditasi aja, tapi juga melihat keseluruhan gimana lingkungannya, apakah layak engga, apakah sudah memenuhi standar mutu.”
“Diperlukan adanya peningkatan kepedulian terhadap risiko bencana dan perlunya sertifikasi standar kelayakan konstruksi yang digunakan menjadi tempat pendidikan dan gunakan SDM yang memadai untuk menjalankan hal tersebut.”
“Menurutku yang paling penting itu active listening tanpa ngejudge. Jangan langsung kasih saran atau bilang "sudahlah, ikhlas aja" justru itu gak baik buat perasaan mereka. Biarkan mereka cerita kalau mereka mau, tapi jangan dipaksa kalau mereka belum siap. Hindari juga pertanyaan yang terlalu invasif atau minta mereka cerita detail traumatis, karena bisa bikin trauma lagi. Cukup tunjukan kehadiran kita, …”
“Peran yg bisa diberikan adalah menjadi relawan yang bersedia menjadi pendengar yang empatik, tidak langsung memberi nasihat, tapi menunjukkan kepedulian dan kesediaan membantu. Misalnya dengan menemani, membantu kebutuhan harian, atau membuat kegiatan yang menenangkan. Yang penting, tidak memaksa korban untuk bercerita jika mereka belum siap.”
“Sebagai mahasiswa psikologi, kita dapat membantu dengan memberikan penolong pertama dari segi psikologi. sebagai masyarakat, ada beberapa komunitas masyarakat yang bertujuan memberikan bantuan bencana bagi para warga yang terkena bencana di Indonesia, contohnya Pena Berkah.”